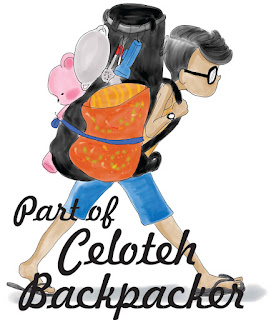Kali pertama
berjumpa dengan masyarakat Bromo atau yang lebih dikenal dengan Suku Tengger adalah
bahasa unik yang mereka pakai. Mereka paham sepenuhnya dengan bahasa Indonesia
namun, jika tengah berbicara dengan temannya, mereka melafalkan bahasa yang
asing terdengar di telinga.
Saya kira
mereka berbahasa Jawa atau Madura. Sebab, di Jawa Timur terutama Surabaya
kental sekali dengan dialek Madura. Bukan, bahasa itu entah dari rumpun apa. Akan
tetapi, jika diperhatikan ada satu dua kata yang terdengar seperti bahasa Jawa.
Mungkin bahasa Jawa Kuno, hehehe... mengingat sejarah Bromo yang sarat akan
Majapahit.
Suku Tengger
sebagian besar menganut agama Hindu yang taat. Tak heran jika di depan rumah
mereka masing-masing terdapat seperti tempat sesaji dari batu. Penampilan mereka
juga unik. Para lelaki biasa memakai sarung yang diselempangkan di bahunya. Tak
lupa pula penutup kepala sebagai penghangat.
Penduduk asli
Bromo ini banyak bermata pencaharian bercocok tanam dan beternak. Sesuai kontur
tanah dan ketinggiannya. Naik ke Bromo berarti melewati jalan berkelok,
berbukit dan menanjak. Di kiri dan kanan terhampar ladang berkebun warganya.
Di tanah
setinggi 2.000 dpl ini tanaman sayur sangat cocok. Namun, tidak untuk tembakau.
Musim kemarau yang datang membuat sayuran banyak yang mengering. Meskipun demikian, mereka bekerja keras untuk
ini demi menghidupi keluarga.
Bromo yang
semakin moncer mendatangkan berkah tersendiri. Mereka tidak menutup diri dengan
dunia luar ataupun orang asing. Yang mereka lakukan justru membuka tangan dan
mempersilakan para wisatawan itu untuk sekadar singgah di rumah mereka. Tak pelak,
selain hotel serta motel, warga setempat menyewakan rumah-rumah dan kamar untuk
ditempati. Mereka juga membuka warung-warung makan yang siap memenuhi perut
pelancong.
Jika tidak
sedang bertani, mereka beralih profesi seperti menjadi pemandu wisata, sopir
jeep, menyewakan kuda dan sebagainya. Salah seorang pemilik kuda yang pernah
saya naiki bercerita, Suku Tengger tidak akan memperbolehkan tanahnya dimiliki
orang lain. Terutama bagi warga China dan keturunannya.
Entah, ada
sejarah panjang apa bagi Tengger dengan saudara jauh Indonesia itu. “Jika ada
yang mau menjual tanah ya dibeli teman sendiri. Pokoknya orang luar tidak boleh
punya tanah di sini,” tuturnya ketika itu sambil menuntun kuda yang diberi nama
Poni.
Menurutnya,
orang-orang itu hanya akan mempekerjaan warga setempat dengan tidak layak. Bisa
jadi, Suku Tengger bakal terusir dari tanahnya sendiri. Begitulah sepemahaman
saya. Maka, dari resor yang paling bagus hingga kelas backpacker sekalipun,
tempat di Bromo ini milik penduduk asli.
Banyaknya wisatawan
yang datang seiring dengan banyaknya kuda yang mereka beli. Penduduk di sana
membeli kuda-kuda itu dari Sumbawa. Harganya pun fantastis, sekitar Rp15juta. Semacam
ada tebus-tebusan untuk mendapatkan kuda yang hebat dan kuat.
Apapun yang
mereka lakukan, ini adalah upaya untuk tetap menjaga kelestarian Bromo. Sejuta bahkan
semilyar orang berkunjung ke Bromo sekalipun, tidak akan mengurangi kadar Suku
Tengger.
Mereka dengan
tangan terbuka menerima tamu-tamu. Senyum-senyum lebar senantiasa tersungging
jika kita berpapasan di jalan. Selalu ada waktu untuk pesan makanan sahur di
tengah umat Hindu ini. Bahkan, mereka bersedia mengantarnya ke penginapan. Jam berapapun!
Tuhan, ciptaanmu keren!
.jpg)

.jpg)