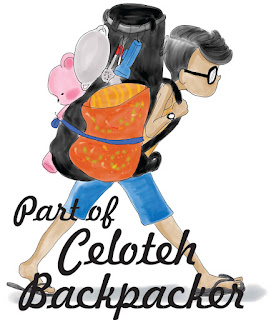Aceh dan kopi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Kurang
lengkap rasanya jika Anda belum merasakan duduk-duduk di warung kopi atau biasa
disebut keude kupi sembari menikmati secangkir kopi asli Aceh jika sudah
menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekkah ini. Sore itu Jumat (10/5) setelah
pulang dari Pulau Weh, saya dan kawan-kawan tergelitik untuk mencoba kopi yang
kata orang paling enak seantero Aceh. Adalah kopi Solong Ulee Kareng yang kerap
menjadi buah bibir karena rasanya yang khas dan istimewa. Ulee Kareng merupakan
nama salah satu kecamatan di Banda Aceh. Maka sambil menunggu bus malam yang
bakal mengantar saya kembali ke Medan, ngopi menjadi hal yang tak akan
terlewatkan.
“Kalau sudah sampai di Banda Aceh, jangan lupa mencoba kopi
Solong Ulee Kareng. Rasanya tiada duanya,” ujar Bang Dendi, seorang teman yang
mengantarkan saya berlima selama di Sabang.
Abang kelahiran Medan, Sumatra Utara ini menganjurkan kami
untuk menjajal kopi Solong. Kurang afdol jika kami tidak mencicipi minuman
berwarna pekat itu. Apalagi sudah sampai di sini. Maka tak perlu berpikir dua
kali untuk menuruti nasihatnya, ngopi.
Sebelum bertolak ke Sabang, kami memang belum merasakan
nongkrong di keude kopi, menghabiskan malam, berkelakar, mengobrol ditemani
harumnya kopi karena keterbatasan waktu. Warung kopi di Banda Aceh memang
menjamur. Kedai-kedai yang menawarkan kopi sebagai sajian utamanya itu mulai
menggelar warungnya sejak sore hingga tengah malam bahkan dini hari. Mereka
membuka lapak menjajar kursi-kursi dengan meja kecil di tengahnya.
Tiba di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, hujan pun
menyambut. Alhasil, matahari yang seharusnya bersinar terik sama sekali tak mau
memperlihatkan batang hidungnya. Untung, mual-mual karena gelombang tinggi air
laut saat saya berada di kapal tak berlanjut ketika berlabuh. Saya berlima harus menunggu sampai setelah
Salat Jumat baru bisa berkeliling Banda Aceh. Waktu-waktu salat memang sangat
sakral terlebih hari Jumat bagi daerah yang pernah diterjang tsunami dahsyat
2004 lalu.